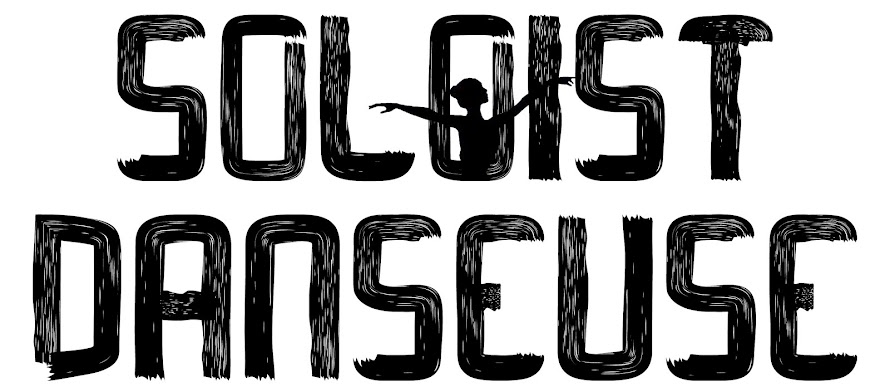"Menikah denganku, maukah?"
Kama tersedak kopi yang baru ia tiup-tiup. Cairan hitam yang masih agak panas membakar lidahnya. Ia meletakkan cangkir putih pualam kopi kembali ke piringnya, memandangi pria di hadapannya. Kedai kopi ini mendadak sunyi, padahal tadi ramai sekali. Mungkin telinga Kama yang mendadak tuli karena pertanyaan yang dilontarkan pria tadi.
Raga, pria yang sudah ia kenal sejak masih menginjak bangku Taman Kanak-kanak. Kehidupan Kama adalah kehidupan Raga. Sejak kecil mereka berdua, bahkan satu sekolah hingga SMA. Kama tahu pada siapa Raga jatuh cinta hingga kemudian patah seadanya. Pun Raga tahu dengan siapa Kama pertama kali memberikan bibir kenyalnya. Serta siapa yang menjamahi tubuh Kama ketika mereka liburan ke Pulau Karimun Jawa bersama-sama.
Menikah adalah salah satu hal yang sama sekali jauh dari kepala Kama. Baginya, mereka sudah lebih dari sebuah pernikahan.
"Untuk apa menikah?"
"Untuk memuaskan dogma yang ada." Jawab Raga.
Kama geleng-geleng. Selama ini ia pikir, mereka sudah dengan sempurna menjadi seorang sahabat bahkan saudara, tidak akan pernah ada lebih dari apa yang mereka sebut teman sejak lama. Tidak ada cinta meski nyaman selalu hadir bahkan ketika mereka diam dan tidak melakukan apa-apa. Pun tidak ada nafsu meski kadang hanya ada di dalam ruangan berdua saja, tidak lebih dari pelukan-pelukan untuk menenangkan kala salah satunya dirundung kesedihan. Meski hadir pula pertengkaran demi pertengkaran, selalu ada kembali serta sambut rentang pelukan.
Tidak ada yang pernah benar-benar saling pergi. Jika satu hilang, salah satunya lagi meninggalkan jejak agar satunya dapat kembali pulang.
Sudah sedemikian lamanya mereka menjalani hal itu, hingga beberapa orang bahkan pacar-pacar mereka cemburu. Namun Raga maupun Kama tidak merasa ada yang aneh dengan hubungan mereka, sejak dulu, ini yang mereka lakukan. Sejak dulu ini kenyamanan yang mereka dapatkan. Sejak dulu, meski pacar sudah berganti dari muda hingga tua sudah di ambang pintu. Mereka selalu seperti itu, pulang yang tidak pernah hilang.
"Kenapa kamu tiba-tiba mau menikah?" Kama masih tidak puas. Pertanyaan dan ajakan nikah dari mulut seorang Raga yang tiba-tiba membuat jantungnya lari keliling kepala.
"Aku mau pulang." Jawab Raga. Matanya sendu, suaranya lelah ketika 'Pulang' terapal dari bibirnya.
Kama tersenyum, contoh senyum seperti teh manis hangat buatan Ibu sebelum kamu berangkat sekolah dulu,"Kamu sudah pulang. Bahkan tanpa harus menikah."
"Aku tahu. Seperti yang aku bilang tadi, memuaskan dogma." Ulangnya lagi. Raga mantap sekali, sorot matanya tegas menyelami manik mata Kama yang jantungnya sekarat hampir tidak bisa berdenyut karenanya.
"Dogma puas, norma? Tidak. Kamu tahu kita tidak bisa menikah di sini."
"Memang tidak di sini."
Raga mengeluarkan sebuah amplop cokelat besar dari dalam tas kerja yang ia bawa lalu menyodorkannya ke dekat tangan Kama.
"Bukalah." Perintah Raga.
Tanpa banyak tanya, Kama meraih amplop cokelat itu dan membukanya.
Mata Kama berbinar begitu menarik lembar persegi panjang pertama yang ia temukan di antara kertas-kertas lainnya. Sebuah tiket. Ke Amsterdam.
Bulir haru berkubang di sudut matanya, lama-lama jadi sungai sampai ke sudut bibir yang kini melengkungkan senyum bahagia.
Di seberang meja Raga tersenyum manis. Ia meraih ujung jemari Kama, ia bawa ke atas meja di balik gelas-gelas kopi mereka. Mata raga menjerat Kama.
"Menikah denganku, mau kah?"
Kama mengangguk.
Mereka berpelukan lewat tatapan mata. Tidak dengan lengan dalam dekapan sebagaimana umumnya, karena Jakarta bukan tempat yang begitu akrab bagi mereka.